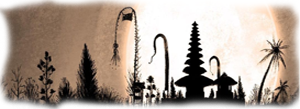Untuk itu Harnity disuruh menyiapkan diri dan segala keperluan administrasi kesulinggihan. Awalnya ada keraguan pada diri Harnity menerima permintaan PHDI, meskipun sebelumnya ia telah berguru pada seorang nabe.
Nabenya tersebut adalah Ida Rsi Bujangga Hari Anom Palguna, dari Griya Batur, Tegalcangkring, Jembrana. Pendidikan spiritual itu dilakukan bersama-sama dengan suaminya, Gede Ardhana Wisnu.
"Namun nasib menentukan lain. Sebelum tuntas pembelajaran itu, pada 2010 suaminya telah lebih dulu dipanggil Tuhan."
Sebelum meninggal suaminya berpesan, kalau bisa, agar proses pembelajaran itu dituntaskan. “Kepikiran oleh wasiat suami, saya terus berdoa agar diberikan tuntunan sehingga diperoleh jalan terbaik bagi kami.
Saban hari kami berdoa, lama-lama kami merasakan ketenangan yang sangat mendalam.
Rasa benci, iri, dendam, dan sebagainya sirna seketika entah ke mana perginya. Sampai akhirnya kami mendapat telepon dari PHDI dan menjalani pediksaan di Denpasar. Semuanya itu di luar rencana saya. Saya pun sempat tak percaya. Kok bisa ya?” tuturnya.
Walaupun sudah mediksa dan sudah bergelar sulinggih, namun dirinya belum berhak ngeloka-palasraya atau muput untuk segala ritual. Kesulinggihan-nya hanya terbatas untuk kalangan keluarga saja.
Ya, Ida Rsi Istri baru “mampu” sebatas nyurya sewana, mejapa, dan mahoma. “Agar bisa ngeloka-palasraya saya masih harus melakukan dua tahapan lagi, yaitu ngelinggihang Weda dan ngelinggihan lingga,” ungkapnya. Ida Istri akan berusaha menggapai posisi itu namun tidak menentukan target. Akan dijalani melalui proses alami dan berharap tetap ada campur tangan dari Tuhan untuk tujuan mulia itu.
Dalam Weda, dia mendapatkan pengetahuan bahwa setiap orang seharusnya pernah melakukan diksa semasa hidupnya. Dia tidak mau setelah mati baru dilakukan diksa.
“Apa artinya kalau sudah jadi mayat baru didiksa?” cetusnya.
Untuk menjadi sulinggih, Edy Harnity tak pernah membayangkan sebelumnya. Jangankan menjadi sulinggih, menjadi Hindu saja tak kepikiran sampai saat usia remaja.
“Ajaran Hindu sebetulnya bagus sekali. Tapi sayang, tidak banyak umat yang mau merujuk dari sastra agama. Kebanyakan umat cukup puas dengan tradisi gugon tuwon.
Sebagai orang yang dibesarkan di keluarga Islam, saya terbawa pada kebisaan merujuk kitab suci, sehingga jika ada yang bertanya tentang sebuah ritual berikut mantramnya, saya bisa menunjukkan sumbernya,” katanya.
Memang sejak kecil hingga tumbuh menjadi dara ayu, dia dibesarkan dan dididik dalam keluarga muslim di Pemalang, Jawa Tengah.
Namun saat melanjutkan pendidikan Sekolah Kebidanan di Semarang, dia bertemu dengan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) asal Banjar (Buleleng, Bali). Mahasiswa Undip yang bernama I Gede Ardhana Wisnu kelak menjadi suaminya. Hatinya saling bertaut saat menuntut ilmu di kota Semarang.
Saat mereka menikah pada tahun 1976, Ardhana Wisna belum menuntaskan kuliahnya. Sementara Harnity, setelah menamatkan sekolahnya, diterima di sebuah puskesmas di Pemalang.
Dengan kata lain, mereka harus lebih sering menahan rindu akibat dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Boleh dikatakan masa bulan madu dilalui dengan banyak tantangan.
Setelah Ardhana Wisnu berhasil menggondol sarjana hukum, Harnity diboyong ke Desa Banjar pada tahun 1978. Di Puskesmas Banjar pula Harnity melanjutkan pengabdiannya. Di Banjar, keluarga anyar itu hanya bertahan dua tahun. Sebab pada 1980 mereka pindah ke RSU Mataram, NTB.
“Saat di Mataram, saya terheran-heran. Sebab banyak umat Hindu yang lahir dari keluarga Hindu justru bertanya kepada saya tentang mantram-mantram. Ini pengalaman aneh. Tantangan di sana lebih besar daripada di Bali.
Umat non-Hindu banyak mengajukan pertanyaan yang bernada melecehkan seperti kenapa umat Hindu menyembah patung. Kalau kita tidak siap dan tidak mampu menjawab, pasti mereka akan semakin merendahkan kita selaku umat Hindu,” tuturnya menceritakan pengalamannya selama 25 tahun di NTB.
Kini setelah menyandang predikat sebagai sulinggih bukan berarti rintangan telah berakhir. Dirinya merasa tertantang dengan sikap skeptis umat yang berhenti pada ritual.
Idealnya, tutur Ida Rsi Istri, antara ritual, etika, dan tattwa berimbang.
Jangan ritual yang lebih ditonjolkan, sementara etika dan tattwa dikerdilkan. Cara-cara yang tak imbang itu menimbulkan persoalan pada umat.
Umat Hindu merasa terbebani dengan ritual yang demikian banyak. Mestinya umat mendapat tuntunan benar agar agama tidak dirasakan memberatkan mereka. “Agar umat Hindu tidak ada yang loncat pagar sebagai akibat beban berat yang mereka rasakan dalam beragama.
Agama seharusnya meringankan mereka. Mereka harus diberikan pembinaan dan pencerahan.
Gugun tuwon jangan biarkan mendominasi mereka,” katanya sambil tidak bisa menyembunyikan logat Jawanya. Kata-katanya sungguh patut direnungkan oleh segenap umat Hindu.
Demikianlah peristiwa terharu tersebut yang diceritakan dalam Pasraman Girinatha yang tak terpikirkan menjadi Hindu, Malah menjadi Sulinggih.
Betapa berkarunianya Tuhan terhadap Edy Harnity. Dari seorang muslim menjelma menjadi Hindu yang tercerahkan dan berlanjut menjadi sulinggih.
Dia tidak tertarik lagi mendengar pernyataan-pernyataan kitab suci yang bersifat dogmatis.
Kebenaran tidak bisa dimonopoli atas nama agama tertentu. Kebenaran agama harus diselaraskan dengan tingkah laku (karma) umatnya.
Karmalah yang menentukan apakah seseorang dapat dikatakan orang baik atau orang jahat. Bukan karena seseorang beragama tertentu.
***